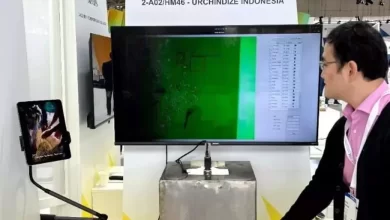Riset menunjukkan ketimpangan emisi lebih nyata terlihat antara kelompok kaya dan miskin. Kelompok terkaya 1% di dunia adalah kelompok penyumbang emisi dengan pertumbuhan paling besar.
Desember lalu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, mendapatkan sorotan karena menggunakan jet pribadi. Kala itu, pasangan selebriti itu bertolak dari Yogyakarta ke Surakarta untuk menghadiri pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Kritik dilontarkan karena keduanya memilih moda transportasi penerbangan yang tinggi emisi gas rumah kaca. Padahal, rute tersebut dapat ditempuh hanya sekitar 60-90 menit melalui jalan darat. Tak hanya Raffi dan Nagita, Katadata (12/12) menyebut PT Angkasa Pura Bandara Internasional Adi Sumarmo memastikan 59 pesawat pribadi para tamu resepsi mendarat dan terbang di Solo. Di Indonesia, penggunaan pesawat pribadi memang belum terlalu banyak menjadi sorotan.
Namun di Swedia, ada istilah ‘flygskam’ yang berarti ‘flight shame’. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada perasaan malu karena terbang. Istilah ini bahkan menjadi gerakan sosial yang mengajak publik untuk mengganti moda transportasi penerbangan, dengan moda lain yang lebih rendah emisi. Ini khususnya untuk mobilitas jarak dekat. ‘Flygskam’ menjadi tren di Benua Eropa. Bahkan di 2019 gerakan ini berkontribusi pada penurunan penumpang penerbangan di Swedia dan kenaikan penumpang kereta api, seperti dilaporkan BBC. Kelompok kaya dan superkaya, yang sering diberitakan atau aktif di media sosial, memang terlihat menonjol. Mereka sering berhadapan dengan ‘penghakiman’ publik.
Apa yang diperlihatkan kini tak lagi diperbincangkan dari tren gaya hidup saja, melainkan juga ke arah isu-isu iklim dan lingkungan. Emisi dan ketimpangan Geopolitik krisis iklim umumnya menyoroti ketimpangan antara negara-negara Utara (Global North) dan negara-negara Selatan (Global South). Tanggung jawab penurunan emisi dititikberatkan pada negara-negara Utara yang menyumbang porsi emisi jauh lebih tinggi dalam periode lebih lama. Harapannya, ini bisa membantu negara-negara Selatan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus rentan dampak krisis iklim untuk melakukan dekarbonisasi dan adaptasi iklim. Di samping ketimpangan antar negara, dalam beberapa tahun terakhir penelitian mencatat bukti-bukti bahwa ketimpangan emisi lebih nyata terlihat antara kelompok kaya dan miskin. Lab Ketimpangan Dunia (World Inequality Lab), dipimpin oleh Sekolah Ekonomi Paris dan Universitas California di Berkeley, mengumpulkan data terkait gaya hidup individu: pola makan, kepemilikan kendaraan, hingga jenis investasi.
Data ini digunakan untuk menghitung jejak karbon mereka. Hasilnya: kelompok terkaya 1% di dunia adalah kelompok penyumbang emisi dengan pertumbuhan paling besar. Emisi mereka 70 kali lipat lebih tinggi dibanding kelompok 50% terbawah. Jika dijumlahkan, kelompok 10% terkaya di dunia (setara 771 juta orang), berkontribusi pada hampir separuh total emisi global (48%), yang secara geografis tersebar di banyak negara. Pada tahun 2020, peneliti di Universitas Leeds juga menerbitkan analisis yang menggarisbawahi perbedaan proporsi emisi kelompok kaya dan miskin.
Dengan semakin bertambahnya penghasilan, orang kaya mengeluarkan lebih banyak uang untuk liburan atau kendaraan. Porsi energi untuk moda transportasi yang dikonsumsi kelompok 10% terkaya mencapai 187 kali lebih tinggi dibanding kelompok 10% terbawah. Ketimpangan emisi ini lebih rendah dan terdistribusi untuk penggunaan energi di tingkat rumah tangga. Analisis serupa pada kelompok superkaya oleh Barros dan Wilk (2021) menunjukkan kesimpulan yang sama. Para milyarder merupakan super-emitters. Lagi, moda transportasi memakan porsi besar emisi yang mereka hasilkan. Pasalnya, mereka tidak hanya menggunakan mobil tetapi juga jet pribadi dan kapal pesiar. Bahkan untuk rute pendek, kelompok super kaya ini sering menggunakan pesawat pribadi. Sementara untuk kapal pesiar, fungsinya lebih sering dipakai untuk liburan ketimbang transportasi. Lima belas dari 20 sampel milyader yang menjadi subjek penelitian ini memiliki superyacht.
Aksi individu atau perubahan sistemik? Guna melakukan transisi energi, kebijakan publik menjadi salah satu pilihan karena menaungi beragam sektor dan kuat menerapkan insentif atau sanksi. Di sisi lain, upaya mendorong perubahan perilaku di tingkat individu dan kelompok juga santer dibahas karena secara kolektif mampu menyulut perubahan sistemik.
Poin ini yang menjadi argumen beberapa ahli bahwa perubahan perilaku dan pengaruh kelompok orang terkaya di dunia, akan mampu berkontribusi pada perubahan sistemik untuk aksi iklim yang lebih kuat dan luas. Nielsen et. al. (2021) menyebutkan kelas sosioekonomi (SES) tinggi (Anda dan saya bisa jadi masuk kategori ini) memiliki setidaknya empat peran non-konsumen sebagai “climate influencer”.
Peran yang dimaksud adalah sebagai investor, teladan atau referensi bagi lingkungan sekitar, bagian dari sebuah organisasi, dan warga negara yang memiliki hak suara dan bisa berkontribusi dalam gerakan sosial. Survei yang dilakukan Institute for Essential Services Reform pada 2019 – 2021 di 7 provinsi di Indonesia menunjukkan hal tersebut. Survei menyebut kelompok SES menengah ke atas bersedia beralih dari listrik saat ini (yang sumbernya didominasi energi fosil) dan menggunakan panel surya.
Salah satunya karena motivasi berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Aksi bisa muncul dari kesadaran, terutama pemahaman sebagai penyumbang emisi, dan karena itu bisa mendorong perubahan perilaku untuk mengurangi emisi. Dorongan psikologis dan tekanan sesama (peer) bisa efektif untuk mendorong perubahan ini. ‘Flygskam’ menjadi contohnya. Begitu pula dengan beralih ke energi terbarukan, menggunakan kendaraan rendah emisi, memilih (dan menuntut adanya) produk-produk yang berkelanjutan, hingga mengalihkan praktik bisnis ke sektor-sektor yang lebih hijau.
Para ahli menyebut fenomena ini sebagai “penularan perilaku” atau behavioral contagion. Pengamatan pemasangan panel surya di rumah yang dilakukan di AS pada 2001 dan 2011 menunjukkan bahwa setiap satu pemasangan baru di dalam satu kodepos dapat memicu kemungkinan pemasangan lainnya dalam 4 bulan, dan lebih cepat lagi setelahnya. Lucunya, pada tahun 2021, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga berkontribusi pada meningkatnya pembicaraan tentang panel surya karena mereka memasangnya di rumah baru mereka. Memang sepertinya belum ada penelitian yang menghubungkan aksi mereka pada minat publik untuk ikut menggunakan panel surya.
Namun, terdapat kenaikan jumlah kunjungan yang signifikan ke website SolarHub.id, sebuah platform yang menyediakan info terkait energi surya dan sejumlah pemasang panel surya. Ini karena salah satu perusahaan di sana menjadi pemasang panel surya di rumah dua pesohor ini. Bahasan panjang ini tentunya bukan untuk mendebatkan aksi individu (atau sekelompok orang) versus kebijakan publik. Bukan juga menihilkan peran korporasi-korporasi besar penyumbang emisi masif.
Justru dengan informasi ini dan ajakan pada kelompok 10% terkaya (di dunia, di Indonesia) dan dengan SES tinggi, kita mendorong munculnya kebijakan publik. Kebijakan ini akan menjadi upaya dekarbonisasi yang berdampak luas dan dibuat dengan melihat kontribusi emisi dan peran tiap kelompok yang berbeda. Lucas Chancel dari Lab Ketimpangan Dunia misalnya, merekomendasikan pajak polusi progresif. Ini termasuk penghapusan subsidi energi untuk kelompok kaya dan aturan ketat untuk pembelian yang ‘berpolusi’ (seperti mobil kesekian dan tiket penerbangan).
Atau mengambil langkah drastis sekaligus seperti Prancis yang baru-baru ini melarang penerbangan untuk kota-kota yang bisa dicapai dengan kereta dalam waktu kurang dari 2,5 jam. Sementara untuk kelompok 50% terbawah, rekomendasinya adalah investasi publik untuk akses energi terbarukan, mengembangkan sistem transportasi publik rendah karbon, dan membangun perumahan rendah emisi. Di sisi lain, jika para climate influencers bersuara dan beraksi, makin kuat pula tuntutan permintaan untuk kebijakan publik yang mendukung dekarbonisasi. Juga pada korporasi untuk mengubah pola bisnis mereka dan meninggalkan sektor tinggi emisi. Makin banyak pula contoh atau referensi gaya hidup rendah karbon, yang harapannya semakin menular ke khalayak ramai.
Marlistya Citraningrum adalah analis senior di Institute for Essential Services Reform (IESR), dengan fokus pada akses energi, kebijakan dan praktik energi terbarukan (khususnya energi surya), energi dan gender, serta inisiatif sub-nasional dan komunitas.